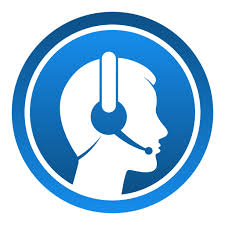Latar Belakang
Mendapatkan keadilan adalah hak bagi setiap warga negara yang bernaung di bawah negara hukum. Pilihan para pendiri negara Indonesia untuk membentuk negara yang berdasarkan hukum membawa konsekwensi timbulnya kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, baik hak yang timbul dari hubungan kontraktual antar sesama warga negara, hubungan kontraktual antara warga negara dengan penyelenggara negara, maupun hak asasai manusia, yakni hak yang timbul karena terlahir sebagai manusia yang dikenal dengan konsep hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.
Dalam rangka mewujudkan keadilan tersebut, perlindungan hukum terhadap warga negara diselenggarakan berdasarkan asas persamaan di muka hukum (equality before law).
Berdasarkan asas ini, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap satu orang atau kelompok masyarakat yang menyebabkan haknya lebih besar dibanding orang tau kelompok lain. Sebaliknya, perlindungan terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada prinsip non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan perlakuan karena faktor-faktor tertentu, antara lain asal-usul etnis, ras, agama dan jenis kelaminnya.
Diharapkan, dengan diberlakukannya asas ini, maka keadilan dapat dinikmati setiap orang.
Namun, pada kenyataannya, kesempatan untuk dapat mengakses perlindungan hukum dan keadilan tidaklah sama antar warga negara. Banyak pengalaman di masyarakat yang menunjukkan adanya kesenjangan akses keadilan antara satu golongan dengan golongan lain. Berbagai penelitian ilmiah telah menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjauhkan masyarakat tertentu dari keadilan, antara lain nilai-nilai sosial budaya yang tidak menguntungkan mereka, minimnya informasi hukum yang melindungi mereka, sulitnya mengakses layanan peradilan karena faktor biaya, jarak dan pengetahuan, serta ketidakseimbangan kekuatan antar pihak-pihak yang berperkara.
Beberapa contoh yang dapat dikemukakan misalnya, adanya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga namun tidak terlindungi oleh hukum. Perempuan dan anak yang dalam banyak masyarakat dikonsepsikan sebagai objek kepemilikan laki-laki seringkali menjadi sasaran tindakan kekerasan oleh laki-laki yang berkuasa dalam rumahnya, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat di sekitarnya juga acapkali memaklumi keadaan tersebut karena menganggap bahwa melakukan kekerasan adalah hak laki-laki untuk mendidik anak dan istrinya. Dalil-dalil keagamaan tidak jarang dimunculkan guna melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya di dalam rumah, kekerasan terhadap anak dan perempuan juga banyak ditemui di sektor publik, seperti tempat kerja, sekolah, angkutan umum, tempat ibadah, dan lain-lain.
Selain perempuan dan anak, orang yang rentang kehilangan akses keadilan adalah orang miskin. Telah banyak kasus-kasus yang mengemukan di media massa bahwa karena kemiskinannya, seseorang mendapat perlakuan yang tegas, kejam dan tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum, namun pada saat yang sama aparat menunjukkan perlakuan yang halus, lembut, sopan, murah hati, tunduk dan mengabdi pada kepentingan orang kaya. Atas nama penegakan dan kepastian hukum, aparat hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim seringkali bertindak sangat tegas, namun hanya kepada orang miskin. Adapun kepada orang-orang kaya, seperti bandar narkoba, koruptor dan pengusaha besar, aparat hukum tampak sangat berhati-hati, melayani mereka sesuai standar hak asasi manusia, bahkan tidak jarang melampaui standar tersebut. Akibatnya, orang-orang miskin menjadi sangat rentan mengalami marjinalisasi oleh hukum, sementara mereka sendiri dalam struktur masyarakat dapat dipetakan sebagai kaum marjinal karena lemahnya kemampuan mereka dalam mengakses berbagai layanan publik. Artinya, hukum tidak selalu dapat berfungsi untuk membantu kaum marjinal untuk mendapatkan keadilan, namun justru berperan memarjinalkan mereka lebih jauh lagi.
Marjinalisasi hukum terhadap masyarakat marjinal sering membingungkan, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi hukum. Tidak sedikit masyarakat yang pesimis terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia akibat mengetahui pengalaman buruk kaum marjinal yang berhadapan dengan hukum. Rasa pesimisme ini terwujud dalam berbagai opini negatif yang memandang bahwa keadilan harus dibeli, pengadilan tidak dapat memberikannya secara gratis, siapa yang dapat membeli, dialah yang akan mendapatkan “keadilan”. Berita tentang mafia peradilan yang melibatkan aparat-aparat tanpa integritas menambah dalam rasa pesimisme dalam masyarakat akan tegaknya keadilan bagi Masyarakat marjinal.
Berpijak dari pemikiran di atas, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung merasa penting dan perlu untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkeadaban, di mana upaya penegakan hukum bukan semata-mata ditujukan demi kepastian hukum, namun yang lebih penting adalah demi menegakan keadilan yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa. Semangat menegakkan keadilan inilah yang ingin kami kobarkan dan tanamkan dalam diri mahasiswa agar dapat memiliki integritas yang kuat untuk menyiapkan diri menjadi calon ilmuwan dan praktisi hukum di masa depan. Sebagai langkah kongkrit, kami bermaksud menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Penegakan Hukum sebagai upaya Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat Marjinal”.